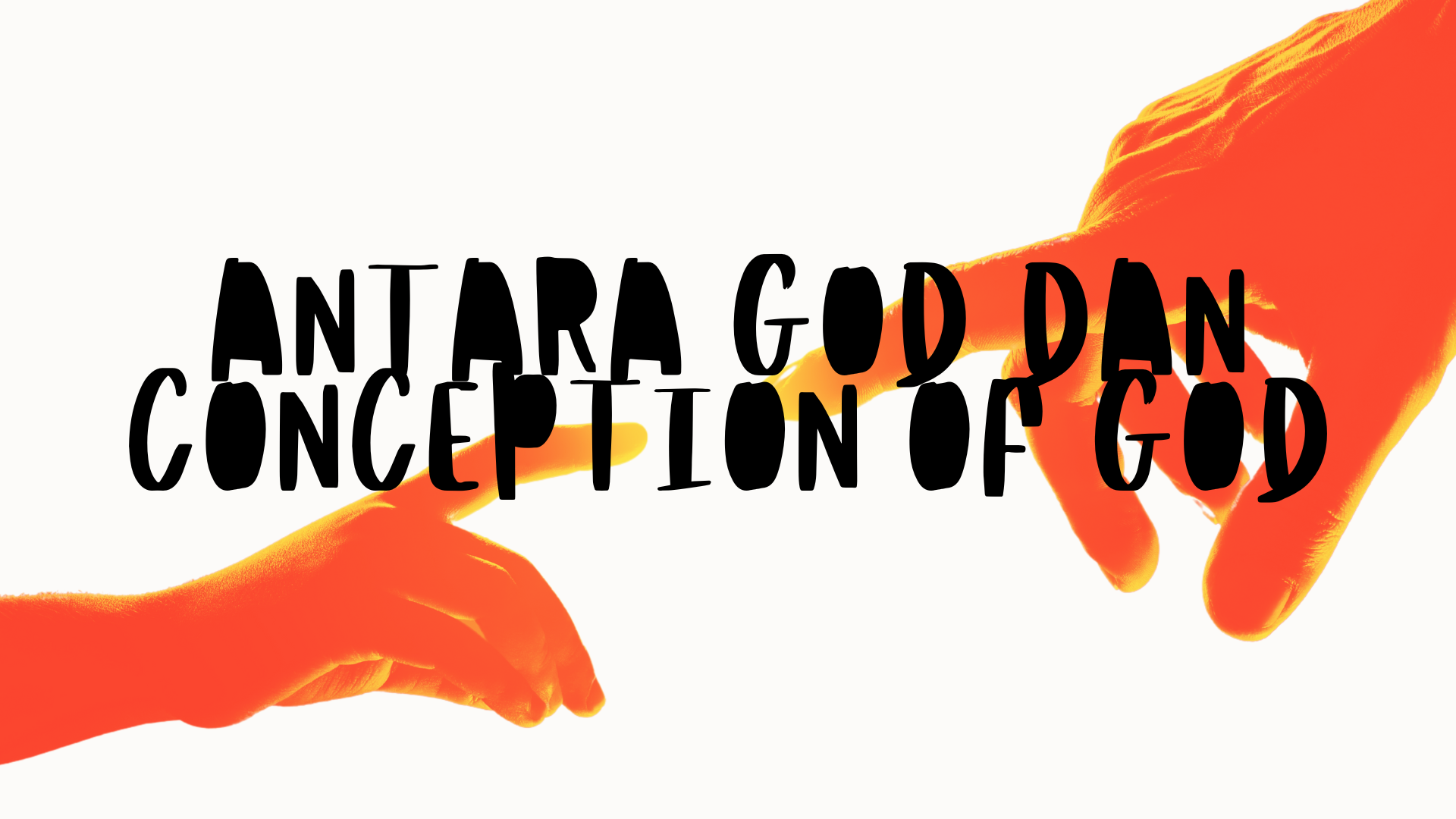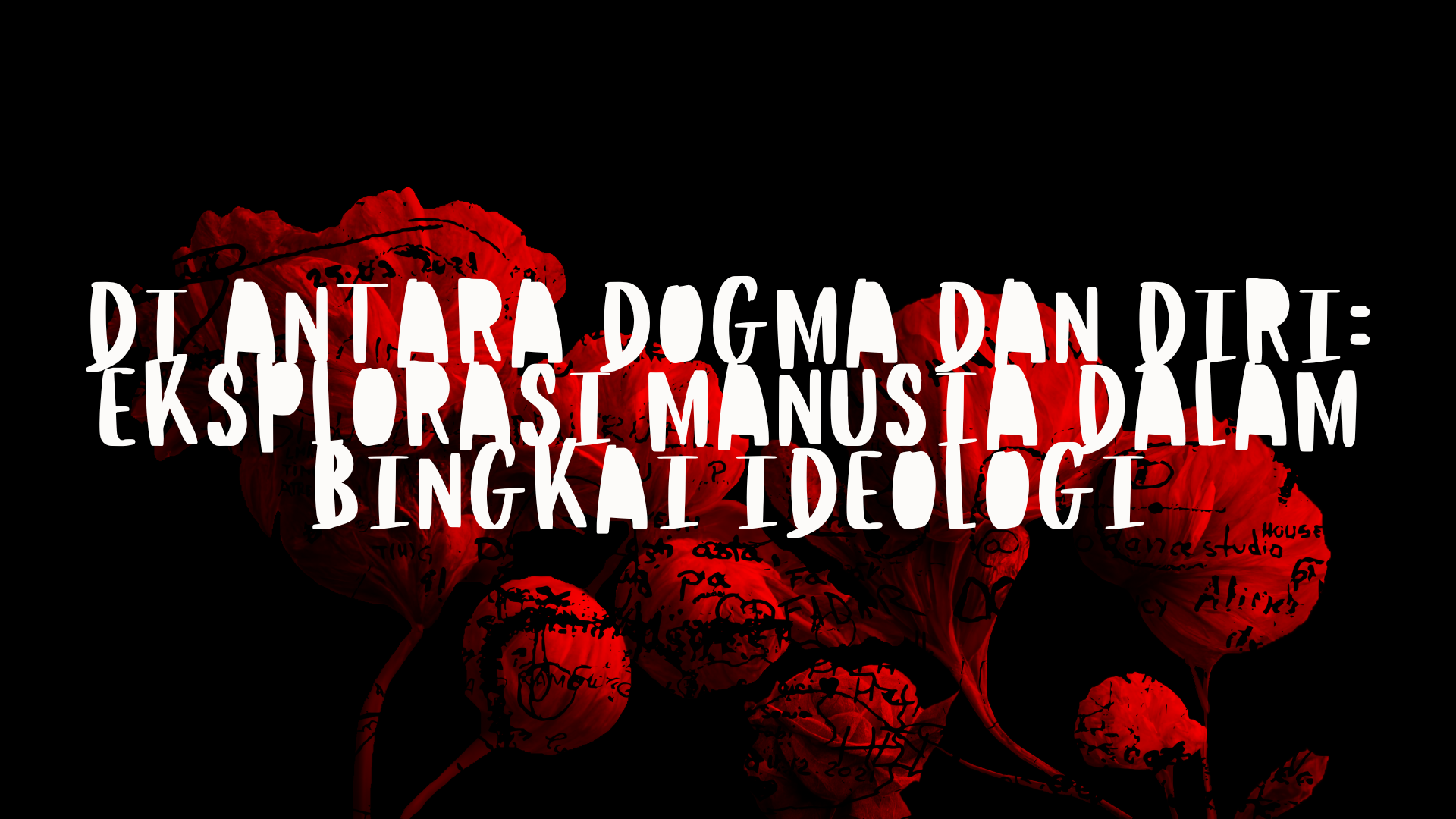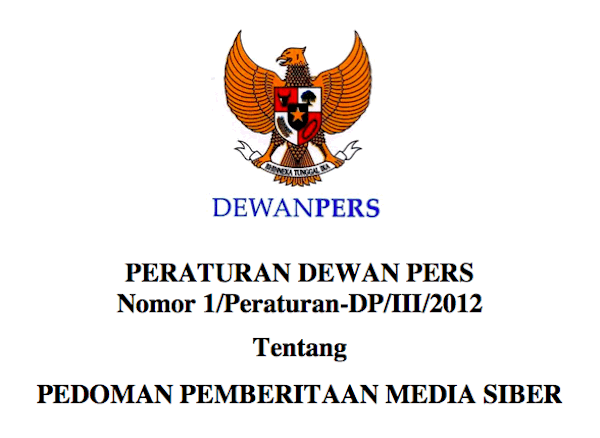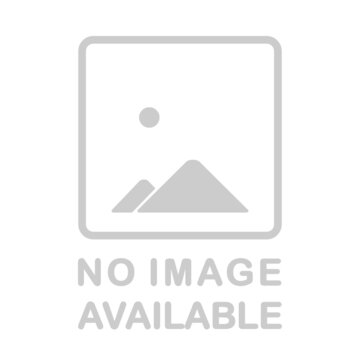Kepercayaan merupakan fondasi fundamental bagi manusia, melahirkan tatanilai yang menopang eksistensi dan budaya. Ketidakpastian inheren dalam kehidupan manusia mendorong individu untuk mencari kepastian melalui kepercayaan, namun kepercayaan yang dianut tak hanya harus memenuhi kebutuhan psikologis, melainkan juga berakar pada kebenaran objektif. Pluralitas kepercayaan yang ada di masyarakat menghadirkan dilema epistemologis: apakah semua kepercayaan itu salah, atau hanya sebagian? Realitas kompleks menunjukkan bahwa setiap kepercayaan mengandung spektrum kebenaran dan kepalsuan yang bervariasi. Nilai-nilai yang lahir dari kepercayaan kemudian mengkristal dalam tradisi, membentuk ikatan sosial yang kuat. Ironisnya, sementara tradisi berperan sebagai penjaga nilai-nilai luhur, sifatnya yang konservatif seringkali menghambat dinamika sosial dan perkembangan peradaban. Dengan demikian, kepercayaan yang seharusnya menjadi pendorong kemajuan justru dapat menjadi belenggu jika terjebak dalam rigiditas tradisi.
Kehidupan sejatinya masyarakat yang menuju sebuah peradaban yang dalam pemaknaan radikalnya adalah sebuah kehidupan masyarakat yang maju, Suatu peradaban seharusnya tidak hanya diukur dengan pencarian material jasa. Tapi ia harus di lihat juga dari pencarian 3 tujuan pokok hidup manusia yaitu ibadah pada Allah, Khalifah dibimi dan isti’mar (Nafis, 2020)
Peradaban manusia merupakan manifestasi kompleks dari interaksi antara masyarakat dan lingkungannya. Perbedaan perkembangan peradaban antar masyarakat dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama. Faktor lingkungan geografis seperti iklim dan topografi secara signifikan memengaruhi pola adaptasi dan produksi masyarakat, membentuk basis material peradaban. Norma sosial dan budaya yang bervariasi antar masyarakat menciptakan kerangka nilai dan perilaku yang unik, mempengaruhi institusi sosial dan praktik sehari-hari.
Stratifikasi sosial yang terbentuk dari perbedaan kekuasaan, prestise, dan akses terhadap sumber daya menghasilkan hierarki sosial yang khas dalam setiap masyarakat. Ideologi sebagai sistem kepercayaan dan nilai yang mendasari kehidupan kolektif menjadi pendorong utama perubahan sosial dan perkembangan peradaban. Agama sebagai salah satu bentuk ideologi memberikan kerangka moral dan kosmologis yang kuat, memengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya, menghasilkan inovasi yang mendorong transformasi sosial dan budaya.
Perumusan kalimat persaksian (Syahadat) Islam yang kesatu: Tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Perkataan "Tidak ada Tuhan" meniadakan segala bentuk kepercayaan, sedangkan perkataan "Selain Allah" memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya, dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai - nilai, itu berarti tunduk pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta segala yang ada termasuk manusia. Tunduk dan pasrah itu disebut Islam.
Dalam mencapai pemahaman kosmologis perihal imaterialisme, diperlukan usaha usaha logis dalam mencapai kosmologis itu, dalam pembahasan perihal keTuhanan, usaha logis yang bisa dicapai salah satunya adalah dengan teori kausalitas, Kausalitas dalam bahasa Arab berasal dari kata al-sabab yang berarti asal (karena), mula, lantaran (hal yang menyebabkan sesuatu). Akibat juga berasal dari bahasa Arab 'aqibah yang berarti akhir atau akibat dari sesuatu. Istilah lain dari sebab dan akibat adalah al-sabab wa al-musabab. Dalam filsafat, istilah sebab adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan sesuatu dan bersifat eksternal dan memberikan jejak pada makhluk tersebut. Kausalitas atau sebab-akibat menurut Lorens Bagus memiliki beberapa pengertian, yaitu:
1. Kausalitas berarti menunjukkan, masuknya suatu sebab atas akibat dan juga hubungan-hubungan yang timbul sebagai akibat kegiatan;
2. Kausalitas adalah terjadinya suatu hubungan melalui suatu sebab yang efisien;
3. Dalam kategori filosofis, kausalitas juga menunjukkan hubungan genetik antar gejala. Salah satu gejala disebut penyebab, yang menentukan yang lain disebut efek atau konsekuensi.
Prinsip kausalitas merupakan realitas penting yang harus diketahui manusia setiap hari. Seperti tangan yang terbakar karena menahan api, atau sesuatu yang basah jika terkena air. Konsep kausalitas mencakup cara berpikir tentang diri sendiri, lingkungan dan seluruh alam dimana manusia hidup dan hubungan antara manusia dan alam itu sendiri. Faktanya, manusia bahkan beranggapan bahwa kesadarannya terhadap dunia dan sebagai khalifah di muka bumi ini setiap saat bergantung pada sebab dan akibat. Menemukan berbagai hubungan antara sebab dan akibat juga memberikan wawasan tentang struktur kausalitas di alam, dan membentuk dasar bagi manusia untuk belajar bertindak secara cerdas di dunia. Mencari tahu penyebab sebenarnya memungkinkan manusia membangun pola struktural kausal, dan membuat prediksi rasional dalam mengambil keputusan dan bertindak.
David Hume berargumen bahwa hubungan sebab akibat tidak dapat dipahami secara murni melalui penalaran apriori. Ia berpendapat bahwa pemahaman kita tentang kausalitas semata-mata berasal dari pengalaman empiris. Dengan kata lain, kita hanya dapat mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara dua peristiwa setelah mengamati secara konsisten terjadinya peristiwa tersebut secara berurutan. Hume menegaskan bahwa tanpa pengalaman, kita tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa adalah penyebab dari peristiwa lainnya.
Secara umum, hubungan sebab akibat dicirikan oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat keterkaitan temporal antara sebab dan akibat, di mana sebab selalu mendahului akibat. Kedua, terdapat hubungan spasial antara keduanya, di mana sebab dan akibat seringkali terjadi di lokasi yang berdekatan. Ketiga, terdapat hubungan yang konsisten, di mana setiap kali sebab terjadi, akibat yang sama cenderung mengikuti. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa hubungan sebab akibat ini bersifat probabilistik, bukan deterministik. Artinya, meskipun kita mengamati pola keteraturan tertentu, selalu ada kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil akhir.
Dalam pembahasan fundamental setelah mengkaji oerihal ideologi, manusia muncul sebagai prantara dari pada ideologi tersebut, manusia yang sejati adalah manusia yang menuju fitrah Konsep fitrah dalam kajian antropologi Islam merepresentasikan esensi kemanusiaan yang unik dan membedakan manusia dari makhluk lainnya. Fitrah bukan sekadar kumpulan sifat atau tindakan, melainkan suatu sistem integral yang terdiri dari berbagai atribut dan perilaku khas manusia. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 menegaskan bahwa fitrah manusia cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Hati nurani, atau dlamier, berperan sebagai kompas moral yang mengarahkan individu menuju kesucian dan kebenaran. Tujuan hidup manusia yang ultimate, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, adalah mencapai kebenaran mutlak atau Tuhan Yang Maha Esa.
Fitrah sebagai fondasi ontologis manusia menjadikannya entitas yang berbeda dari makhluk lainnya. Ketika seseorang mengikuti tuntutan hati nuraninya, ia berada dalam keadaan fitrah dan merealisasikan potensi kemanusiaannya secara utuh. Konsep amal atau kerja dalam Islam menegaskan bahwa nilai-nilai luhur tidak hanya bersifat abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Al-Quran mengajarkan bahwa nilai hidup seseorang ditentukan oleh kualitas amalnya. Amal perbuatan yang berlandaskan fitrah, yaitu sesuai dengan tuntutan hati nurani, akan membawa kebahagiaan bagi individu dan masyarakat. Sebaliknya, tindakan yang bertentangan dengan fitrah akan menimbulkan penderitaan. Dengan demikian, fitrah menjadi acuan etis dalam menilai tindakan manusia. Konsep fitrah juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu hingga masyarakat, dan menjadi landasan bagi pengembangan etika dan moralitas.
Dalam mencapai interpretasi dari pada ideologi manusia itu sendiri diperlukan sebuah ikhtiar yang akan bermuara pada takdir, Kemandirian individu dalam menjalankan tindakan sukarela merupakan prasyarat mutlak bagi manifestasi keikhlasan. Kebebasan memilih yang sejati, tanpa tekanan eksternal, memungkinkan seseorang untuk menyelaraskan tindakannya dengan nilai-nilai moral yang diyakini. Keikhlasan, dalam konteks ini, bukan sekadar tindakan tanpa pamrih, melainkan ekspresi autentik dari potensi kemanusiaan yang tumbuh secara organik dari kemauan baik. Ia merupakan cerminan sejati dari esensi manusia, baik dalam kehidupan duniawi maupun akhirat.
Konsep keikhlasan mengindikasikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas segala amal perbuatannya. Tanggung jawab ini bersifat personal dan kolektif, di mana tindakan seseorang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada lingkungan sosialnya. Dalam perspektif keagamaan, konsep ini diperkuat oleh pemahaman bahwa amal perbuatan akan berbuah pahala atau dosa yang akan dipertanggung jawabkan secara individual di akhirat. Dengan demikian, keikhlasan menjadi landasan etis yang menghubungkan tindakan manusia dengan konsekuensi moralnya, baik dalam kehidupan duniawi maupun akhirat, Manusia tidak dapat berbicara mengenai takdir suatu kejadian sebelum kejadian itu menjadi kenyataan. Maka percaya kepada takdir akan membawa keseimbangan jiwa tidak terlalu berputus asa karena suatu kegagalan dan tidak perlu membanggakan diri karena suatu kemunduran. Sebab segala sesuatu tidak hanya terkandung pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada keharusan yang universal itu